 Ilustrasi(Dok FH UII)
Ilustrasi(Dok FH UII)
SEJUMLAH pakar Ilmu Hukum, hari Sabtu menggelar eksaminisasi putusan terhadap kasus Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Eksaminasi yang digelar Centre for Leadership and Law Development Studies (CLDS) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonsia Yogyakarta ini secara khusus menyoroti putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Tom Lembong dalam perkara impor gula tahun 2015.
Hasil eksaminasi menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim dinilai cacat hukum, lemah dalam pembuktian, dan berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan administratif dan tindak pidana korupsi.
Kebijakan atau Kejahatan?
Eksaminasi ini menghadirkan sejumlah pakar hukum terkemuka seperti Prof. Dr. Rusli Muhammad, Prof. Dr. Ridwan, Prof. Dr. Hanafi Amrani, dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Diskusi berlangsung hangat, penuh argumen akademik yang tajam dan berlandaskan pada prinsip keadilan substantif.
Menurut Dr. Muhammad Arif Setiawan, tindakan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 seharusnya dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan administratif dalam konteks diskresi, bukan perbuatan pidana.
“Jika kita menilik substansi perkara, tindakan Menteri Perdagangan saat itu bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan diskresi administratif yang didorong oleh kepentingan publik,” ujar Arif.
Dikatakan, pada masa tersebut pemerintah tengah menghadapi situasi genting akibat gejolak harga gula di pasar domestik. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi agar Kementerian Perdagangan mengambil langkah cepat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. “Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai Menteri, Pembantu Presiden menjalankan mandat Presiden. Ia bukan bertindak atas kehendak pribadi, apalagi dengan motif memperkaya diri atau orang lain,” kata Arif.
Ia kemudian menegaskan sistem presidensiil, kebijakan seperti itu merupakan tanggung jawab politik dan administratif Presiden, bukan pidana yang bisa dibebankan kepada pejabat pelaksana.
Langgar Asas Ultimum Remedium
Dalam eksaminasi tersebut juga muncul kritikan tajam dari FH UII adalah bahwa penegak hukum terlalu cepat menggunakan hukum pidana untuk menjerat tindakan administratif. Padahal, kata Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Ridwa, dalam teori hukum modern, pidana adalah ultimum remedium yakni jalan terakhir ketika seluruh mekanisme hukum lain tidak lagi memadai. “Hukum pidana seharusnya menjadi rem terakhir, bukan alat utama dalam menyelesaikan pelanggaran birokrasi,” jelas Prof. Ridwan.
Pelanggaran prosedural dalam administrasi publik, imbuhnya seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik dan administratif, bukan langsung dipidanakan. “Jika setiap kesalahan administratif dikriminalisasi, maka keberanian pejabat publik untuk bertindak cepat dalam situasi krisis akan lumpuh,” tambahnya.
Hal lain yang disorot dalam sidang eksaminasi adalah dasar pembuktian kerugian negara yang digunakan oleh majelis hakim. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar potensi. “Dalam kasus ini, klaim adanya kerugian negara berasal dari laporan audit BPKP, bukan dari lembaga resmi BPK,” jelas Prof. Rusli Muhammad.
Padahal, katanya laporan BPKP bersifat administratif, bukan yuridis. "Itu tidak cukup kuat untuk membuktikan kerugian negara secara hukum," katanya lagi.
Jika dasar pembuktiannya rapuh, maka seluruh konstruksi delik menjadi tidak berdiri kokoh. Ia kemudian mengingatkan penegakan hukum tanpa dasar pembuktian yang solid berisiko menimbulkan ketidakadilan sistemik.
Diskresi yang Disalahartikan
Konsep diskresi pejabat publik juga menjadi isu penting dalam forum tersebut. Menurut Prof. Hanafi Amrani, diskresi merupakan ruang hukum yang diberikan kepada pejabat untuk mengambil keputusan dalam keadaan mendesak atau ketika peraturan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan publik. “Dalam situasi tertentu, pejabat publik harus mengambil keputusan cepat. Itu bukan bentuk penyimpangan, melainkan ekspresi dari tanggung jawab jabatan,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, dalam praktik penegakan hukum, diskresi sering kali disalahartikan sebagai pelanggaran hukum. “Ketika setiap inisiatif pejabat dianggap penyimpangan, maka birokrasi kita akan lumpuh oleh ketakutan,” katanya.
Dr. Arif Setiawan menambahkan bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan publik merupakan gejala berbahaya dalam demokrasi. “Bagaimana pejabat publik mau berinovasi atau mengambil keputusan berani kalau setiap langkah kebijakan bisa berujung pidana?” ujarnya.
Ia menegaskan hal ini bukan sekadar soal Tom Lembong, tapi soal masa depan tata kelola pemerintahan yang rasional dan berkeadilan.
Menurut dia, jika aparat hukum gagal membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana, maka penegakan hukum tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan berubah menjadi alat ketakutan bagi birokrasi.
Sementara terkait dengan abolisi, Dr. Arif menilai bahwa secara hukum, dengan adanya abolisi, perkara tersebut sudah semestinya dianggap selesai.“Kalau saya pribadi menjawabnya, dengan adanya abolisi itu kan perkaranya dihentikan prosesnya,” jelasnya.
Penghentian melalui abolisi itu, ujarnya diberikan ketika Tom Lembong sudah mengajukan banding sehingga perkaranya menjadi "belum berkekuatan hukum yang tetap atau belum inkrach.
Dengan demikian, menurut Arif, pemberian abolisi oleh Presiden otomatis menghentikan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “Dengan adanya abolisi itu, ya sudah selesai,” tegasnya.
Namun kemudian timbul pertanyaan yang masih harus menunggu jawaban adalah nasib sejumlah orang yang kini diadili dalam kasus yang terkait dengan Tom Lembong.
Sebagai penutup, para akademisi FH UII sepakat untuk merekomendasikan agar putusan terhadap Tom Lembong ditinjau ulang, baik melalui mekanisme upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), maupun melalui evaluasi etik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Mereka juga mendesak agar pemerintah dan DPR memperjelas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, agar penegakan hukum tidak lagi menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat publik. “Keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memahami konteks,” ujar Prof. Ridwan. “Ketika hukum berhenti memahami, maka yang lahir bukan keadilan, melainkan ketakutan,” ujarnya. (H-2)

 1 month ago
15
1 month ago
15








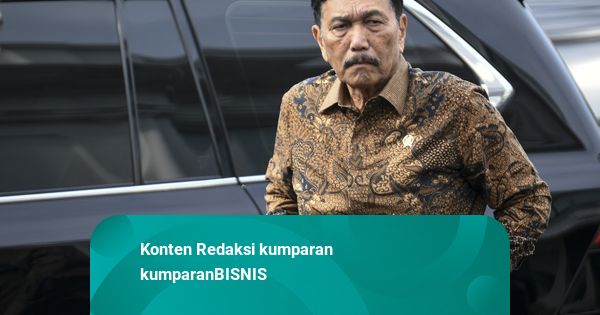












:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5276828/original/024798900_1751964665-WhatsApp_Image_2025-07-08_at_14.47.05.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5357242/original/017691500_1758523929-IMG_20250922_110751_383.jpg)
![[Kolom Pakar] DR dr Zainy Hamzah: Reformasi Tarif JKN, Akhiri Efisiensi Semu](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/txsBxxFQ_uivw0AQ-2jrHY51ND8=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5370153/original/026829600_1759492796-IMG_7766.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5377050/original/026970200_1760074385-IMG_8595-01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5377312/original/048394600_1760088267-iPhone_17_Series_01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5373448/original/026858900_1759822492-WhatsApp_Image_2025-10-07_at_10.03.07.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5369104/original/016390500_1759419694-WhatsApp_Image_2025-10-02_at_14.06.06.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5371392/original/001361000_1759651139-JWC_2025_0.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5372786/original/063502200_1759763740-WhatsApp_Image_2025-10-06_at_19.06.48_b3aa4b10.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5368928/original/033694500_1759400122-WhatsApp_Image_2025-10-02_at_16.54.13__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5372596/original/015905500_1759746592-Legion_Pro_5i_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5366183/original/028563300_1759219654-Xiaomi_17_Pro_dan_17_Pro_Max.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5369745/original/043897200_1759479019-Screenshot__72_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5381343/original/033703500_1760501307-Cara-Arsitektur-AI-Native-ERP-ScaleOcean-Pastikan-Analisis-Data-Bisnis-Akurat.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5142849/original/091530300_1740474739-Mengurangi_Stres.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5374973/original/010734000_1759908322-copy_4f8ac437-abb3-4c05-8ab2-82f03693299c-9915dc.jpg)
![[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Wamenkes Baru dan Eliminasi Tuberkulosis](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/y0KuB7erhDJ6TbtDuKZCqONsZYw=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5376817/original/095760700_1760054336-WhatsApp_Image_2025-10-09_at_4.52.47_PM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5376308/original/081655500_1759999439-Anggota_Alzheimer_s_Indonesia_memberikan_peragaan_tentang_poco-poco_ceria.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3443990/original/029997800_1619751921-elsie-zhong-agevLQdxwts-unsplash.jpg)